Islamisasi sains : sebuah upaya mengislamkan sains Barat modern
Dahulu, antara ilmu dengan agama tidak terpisah. Bahkan ilmu bagian dari agama, karena agama mengajarkan pentingnya menuntut ilmu. Dalam Islam, wahyu pertama berupa perintah “membaca” yang artinya juga “berilmu”. Hanya saja, ilmu yg dituntut dalam Islam adalah ilmu yang berketuhanan. “Iqra’ bismi rabbikaladzi khalaq. Bacalah (berilmulah) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.” (QS al-Alaq: 1) Para ulama dan saintis muslim jaman dahulu tidak pernah memisahkan ilmu (science) dari nilai2 spiritual keagamaan dalam aktivitas ilmiahnya. Dalam kitab al-Jabbar wal Muqabalah, Ibnu Musa al-Khawarizmi (850-780 M) memulai kitabnya dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, lalu memuji Allah dan bershalawat kepada Nabi. Padahal kitab al-Jabar adalah kitab tentang persamaan matematika (sekarang menjadi bagian dari mata pelajaran matematika). Abu Bakar Zakaria ar-Razi (925-854 M) dalam kitabnya Sirr al-Asrar, sebuah kitab tentang farmakologi, ketika menjelaskan pembuatan larutan polisulfida mengakhiri alineanya dengan kalimat “dan Allah Maha Tahu apa yg terbaik”. Dan tentu masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Lalu dengan kemunduran peradaban Islam di abad 16 M, perabadan Barat bangkit dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Hanya saja, ilmu dan sains yg dikembangkan Barat bersifat sekuler, yaitu memisahkan agama dari dunia (fashlu ad-din anil hayah), termasuk ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang awalnya dari Islam dibaratkan (westernized) dan disekulerkan (secularized). Meskipun dunia saat ini banyak mendapatkan keuntungan dari ilmu pengetahuan yang dikembangkan Barat, tapi tak sedikit dengan kerusakan yang ditimbulkannya. Maka, mulailah kesadaran dari para cendekiawan muslim untuk mengembalikan ilmu pengetahuan Barat dengan melakukan dewesternisasi ilmu atau dengan kata lain Islamisasi ilmu (sains).
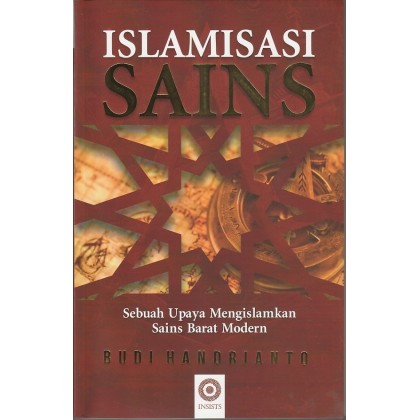
اشتراک گذاری
/